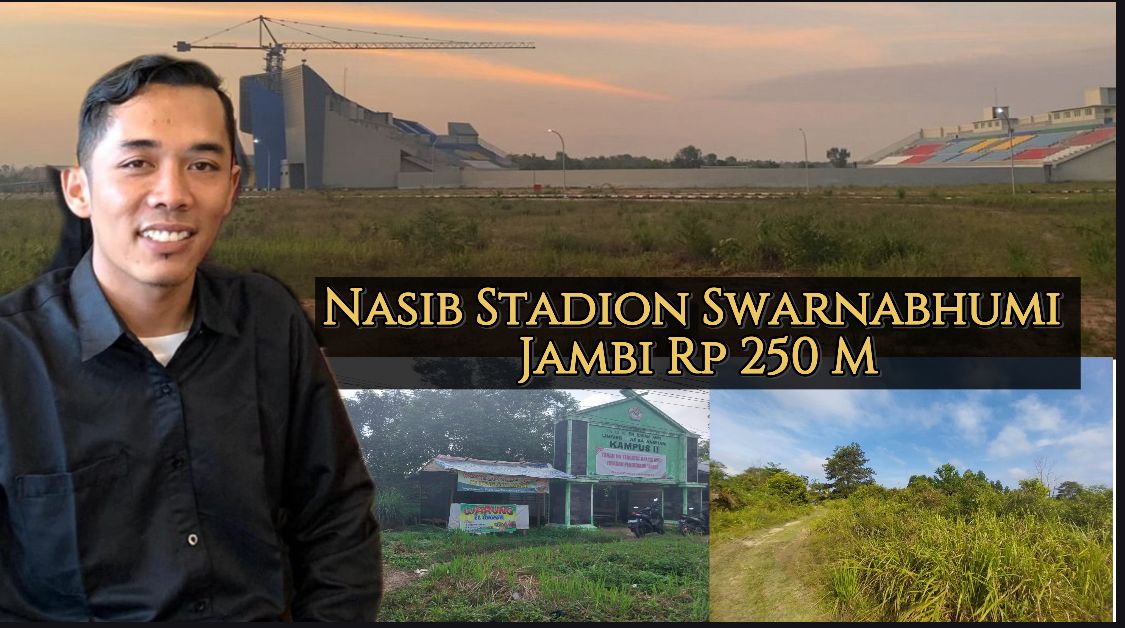(Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Sungai Penuh)
PANCASILA SEBAGAI TITIK TUMPU
Oleh: Indra Mustika. (Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Sungai Penuh)
Pancasila Sebagai Titik Tumpu
Saya mencoba mengelaborasi (menggarap) pemikiran yang hari ini memiliki sublim moral berbangsa, ditengah kehiruk-pikukan gelombang pragmatisme-oportunis berbangsa, namun selalu ada pijar pencerahan yang lahir dari kemarlip bintang-bintang keindonesiaan, iatu Dr. Yudi Latif dengan buku Wawasan Pancasila (2018) dan Negara Paripurna. Buku Dr. Yudi Latif “Wawasan Pancasila” saya ambil sebagai titik tumpu melihat realitas kebangsaan hari ini.
Sebelumnya Dr. Yudi Latif menjabat sebagai Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, namun karena integrity memungkinkan seorang moralis terpental melihat arus disoreantasi kebangsaan, sehingga beliau mundur. Sebuah ungkapan ketika beliau mundur dengan metafor yang sangat dalam “Ibarat Buih Di Lautan, Menggembung, kemudian pecah menyatu dengan kembali pada (asal) air lautan”. Itu pemaknaan yang sangat bermakna, bagi saya, seorang moralis, tahu kapan dia akan menggelembung dan kapan dia akan menyatu dengan pembumian diri pada realitas kemanusiaan Indonesia.
Pancasila adalah satu-satunya cara melihat Keindonesiaan hari ini yang relatif objektifismenya di percaya. Kepercayaan di dasari oleh kesepahaman dan kesepakatan anak bangsa dalam (sejarah) Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam ungkapan Yudi Latif dalam buku Wawasan Kebangsaan dengan mengutip pendapat Francis Fukuyama (1995). “Kemakmuran suatu bangsa, dan juga kemampuannya untuk berkompetisi di pasar global, dikondisikan oleh suatu karakteristik kultural yang bersifat pervasif, yakni tingkat “percaya” (trust) yang secara inheren ada dalam masyarakat tersebut”.
Pancasila yang telah terumuskan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia “memaksa” secara moral, intelektual dan laku kepada semua manusia Indonesia termanifestasikan, tidak lagi (ada) perdebatan yang justru akan membonsai kealiman para tokoh bangsa yang telah bersepakat demi persatuan kebangsaan. Namun, kita boleh “berdebat” dalam ranah tafsiran Pancasila sebagai teks dan Pancasila sebagai konteks. Tapi, hanya dengan percaya kita bisa beranjak memahami realitas dan idealitasnya. Jika (sebagian) warga Indonesia masih belum percaya, maka keterjebakan dalam pusaran kubangan (kedangkalan) sepakat dan tidak tentang “Pancasila.
Kemudian, meneruskan (pikir) kata-kata saya, akan saya ambil kerangka dari Dr. Yudi Latif; Titik temu, titik tumpu, dan titik tuju. Ini sebagai kerangka analitik dan kemudian saya akan mencoba merangkai kata-kata dalam kebeningan pikiran dan keheningan perenungan; agar mendapat kedalaman memahami Pancasila dalam rangka sumbangan ide dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke 77.
Dalam memahami Pancasila kita akan kehilangan arah penuntun jika kita belum memahami kerangka (cara) paham, maka keurgensian kerangka (titik temu, titik tumpu dan titik tuju) menjadi perspektifisme. Terjelaskan atau tidak (masih belum urasan saya) tapi terpercaya atau tidak, akan menjadi (masih) ikhtiar saya.
PERCAYA?
Masihkah kita percaya Pancasila sebagai sumber pemecahan masalah kebangsaan hari ini? Apa yang membuat kita percaya? Untuk apa “percaya” penting dan makna? Jika realitas Indonesia memiliki titik kesenjangan yang lebar dengan Idealitas Pancasila, apa kita tetap percaya?
Semua pertanyaan di atas adalah bentuk merefleksi pemahaman (saya, anda dan kita) tentang “pra paham” ke-Pancasilaan. Merajuk serpihan pemahaman akan di arahkan kepada titik selisih dan titik sentesis. Kendati nantinya dalam mencoba mengurai jawaban tidak terjawab sepenuhnya karena memang memakan waktu dan kata-kata yang panjang bahkan bisa di jawab dalam satu buku.
Semua manusia Indonesia berhak bertanya tentang apa yang ingin di percaya, karena dasar kepercayaan bukan karena “tidak paham” baru yakin, karenanya tapi percaya atas dasar “minimal sedikit tahu” walau lebih baik “kelimpahan tahu” seperti Dr. Yudi Latif.
Kemudian kita harus yakin juga bahwa kita “belum tahu”, ini bisa meyakinkan kita terawal bahwa ada ruang kosong yang bisa kita isi dengan perenungan tulisan ini, namun jika sudah tahu, jadikan ini sebagai komperasi dengan membuka ruang dialektika bak seperti persilangan kayu yang membuat “api” Pancasila bisa menyala dalam pikiran kita.
Percaya, pada dasarnya, bisa kita lihat dari arti kata “believe” dan “trust” menurut Oxford Dictionary adalah, “menerima suatu hal sebagai hal yang benar dan nyata, meskipun tanpa adanya bukti.” Nah, kosakata yang termasuk ke dalam kata kerja atau “verb” ini bermakna “percaya” dalam bahasa Indonesia.
Mempercayai “Konsep” memang sulit, namun lebih menyulitkan jika kita tidak mencoba memikirkan tentan “paham”. Paham yang ingin kita maksudkan, bahwa segala hal terkait ke-Pancasilaan; historis, teoritis, filosofis dan ke-realita-an. Dengan cara ini kita dipandu menuju relatif paham.
PANCASILA; TITIK TEMU (II)
Pancasila sebagai marcusuar moral kebangsaan, dianyam dalam tali persaudaraan kemanusiaan, merawat keperbedaan suku, puak, etnis, agama, dan bahasa dalam payung persatuan Indonesia. Berbeda dalam persatuan dan menggembirakan persatuan dalam perbedaan. Memahami ini tidak semudah membaca kalimat itu, namun keinsyafan dan pengetahuan ke-bhineka-an, kemajemukan dan multikulturalisme keindonesiaan adalah sebuah “keniscayaan” prasyarat ke ke-tunggal ika-an. Pengetahuan “ke” juga menjadi penting. Bagaimana proses kesadaran dan titik (etis-logis) temu dalam keranjang kebangsaan yang dimaksudkan oleh ke-tunggal-ika-an.
Nalar-etis Pancasila merupakan sisi sentesis yang bisa kita gali sebagai titik sama kebangsaan. Bahwa kesepahaman kita berikhtiar dalam mewujudkan persatuan Indonesia, keadilan, kemanusiaan dan hikmat permusyawaratan. Tidak ada sebuah Negara Bangsa yang mampu merdeka atas keterpecahan horizontal dan menyembuhkan penyakit bangsa dari korupsi, nepotis, kolusi dan gesekan sosial kecuali kemampuan mengerti moral etis dalam persatuan kemanusiaan universal yang terbumikan.
Dalam kerangka keindonesiaan kemanusiaan kita tinggikan dan keadaban kita ketengahkan dan peradaban kita majukan. Setiap persoalan sentimensi agama baik inter maupun lintas iman, harus di tekan sampai pada titik nol, karena setiap prasangka anak bangsa karena perbedaan “iman” dan komunitas akan potensial menyulut api sosial yang membakar keindonesiaan kita. Maka, segala perbedaan; kita tinggikan sikap toleransi, inklusi, dan demokrasi, sehingga keharmonisan dalam pergaulan sesama anak bangsa mampu menciptakan simfoni Indonesia yang indah dan penuh ramah.
Dalam perjumpaan anak bangsa dilandasi moral yang sama, penegakan dan pendistribusian “keadilan sosial”. Hal diisyaratkan John Raws yang di kutip dalam buku Yudi Latif Wawasan Pancasila (2018); “Sumber persatuan dan komitmen kebangsaan dari negeri multikulturalisme ialah konsepsi keadilan bersama”. Sila keadilan sosial menjadi peran signifikansi dalam berbangsa. Jika terjadi pengabaian moral-etis-logis ini akan berimplikasi pada kerenggangan kehidupan multikulturalisme Indonesia. Untukmenjahit kain persatuan akan membutuhkan ruang dan ongkos yang besar.
Titik sentral moral kita adalah keadilan sosial. Segala ikhtiar kebangsaan yang dikelola oleh Negara harus mencerminkan keadilan sosial. Perbedaan tidak untuk di benturkan dan juga tidak untuk di segregatifkan dalam konteks sosial politik, serta pengabaian terhadap imparsialitas. Namun perbedaan untuk diharmonisasi dan disinfonikan menjadi kekuatan dan keberadaan yang mengkristal untuk merawat dan menjaga keindonesiaan.
Persoalan kita sila ke lima masih mengawan seperti yang di ujarkan oleh alm. Buya Syafii Maarif setiap ceramah kebangsaan “bahwa Pancasila terutama sila ke lima telah lama menjadi yatim piatu”. Pesan moral ini luar biasa, tersirat pengabaian dan ketidakpedulian pada keadilan sosial. Banyangkan, kesenjangan sosial kita lebar sekali, kemiskinan semakin mengerikan, bahkan keadilan hukum semakin tumpul keatas. Sebuah pernyataan mengejutkan juga saat acar Indonesia Lawyer Club yang dimoderatori oleh Karni Ilyas, Prof. Mahfud MD terang-terangan menyampaikan kondisi transaksi hukum terjadi.
Degradasi esensial dari hukum terjadi oleh anak bangsa yang tuna moral dan buta sosial. Krisis moral bermula mengambil istilah Yudi Latif “Lilucuti sekedar penjaga malam, ekonomi dikendalikan mekanisme pasar.” Kebebasan ekonomi pasar bisa berdampak pada kebebasan individu untuk mengkapitalisasi kekayaan. Ini sikap predator yang lambat laun menghabiskan “mangsa” karena sumber penindasan ekonomi.
Seorang ekonom Joseph Stiglitz mengatakan “inkompetensi dari pihak pengambil keputusan dan merangsang ketidakjujuran dari pihak institusi finansial”. Ini persoalan disaat kekuatan ekonomi mengoreantasikan semata-mata bisnis maka pengabaian terhadap kompetensi dan ketidakjujuran terjadi. Bahkan hukum di kendalikan oleh korporasi. Transaksi perkara dan perundang-undangan bisa terjadi demi melegalkan proses pasar yang tidak adil.
Ketidak adilan pasar ini berakibat buruk pada perekonomian, sehingga kemiskinan semakin melebar karena dikenadalikan oleh korporasi dan orang kaya. Kemiskinan akan menyulut kriminalitas ditengah kehidupan bangsa, karena tidak hanya persoalan makan namun persoalan aman dan kelangsungan. Keterancaman akan meresistensi secara kejam, begal sampai membunuh, pencurian, perampokan di Rumah Orang kaya kemudian dibunuh, pelecehan, dan penjarahan tanpa kemanusiaan.
NARSISME PERAYAAN KEMERDEKAAN (III)
Saudaraku, jika dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia hanya dalam sebatas narsis, maka potensial kekaburan refleksi dari kemerdekaan terjadi. Kehilangan “jasmerah” dalam ungkapan terkenal Bung Karno; “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah”, jika anak bangsa lupa akan sejarahnya sendiri, maka berakibat tereduksi patriotisme kebangsaan hari ini. Karenanya persoalan “narsisme” tidak hanya dilihat dari serimonial perayaan namun ketidak hidmatan memahami perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Mengapa harus narsisme? Sesungguhnya pertanyaan ini bisa terjawab oleh kaum ‘narsis” yang sering membangun “citra” diri dalam ruang digital, dan ruang sensasional. Narsisme juga sering di idap oleh politisi, membangun citra diri dalam membangun persepsi publik tentang diri mereka tentang; “saya cinta bangsa” namun “perilaku kebangsaan”?
Kelenturan itu bukan karena Perayaannya, namun persoalan penghayatan dan penghidmatan tentang “Kemerdekaan Republik Indonesia”. Kita tidak mungkin bisa merasa “hidmat” dan “hayat” jika ruh perjuangan dan historis kemerdekaan tidak pernah terbaca oleh anak bangsa yang mengidap (penyakit) narsisme.
Kemerdekaan di raih dengan segala perjuangan dan pengorbanan,.tumpah darah dan nyawa para pahlawan bangsa sebagai pengorbanan dalam merebut kemerdekaan. Sebuah “keselesaian” pada diri mereka tentang “kemiskinan” tidak pernah berpikir bagaimana meraut keuntungan dari materisme kepamrihan Perjuangan Kemerdekaan. Dengan keluasan dan kehalusan batin pahlawan Bangsa sehingga perjuangan mereka tidak bisa di nilai oleh materi dan bahkan “apresiasi” apapun. Hanya Allah, Tuhan yang tahu cara untuk membalasnya.
Tatkala “Gong” Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di tabuhkan pada 17 Agustus 1945, segenap batin keluasan dan kelegaan Manusia Indonesia seketika nyala dan “hayat” merdeka. Kita bisa membayangkan betapa “selebrasi” kemerdekaan Indonesia saat itu di ekspresikan. Ini sebuah keluapan dari suasanan terbebaskan dari tekanan penjajahan dan segala “tirani” kemanusiaan. Suatu hal yang bisa kita “fantasikan” betapa kemerdekaan telah merubah mental Keindonesiaan dari segala kebiadaban penjajahan menuju kemerdekaan dan kebebasan.
Spektrum Suara Proklamator Soekarno telah menyentuh jiwa-jiwa kemerdekaan anak bangsa saat itu. Jiwa yang terhubung dengan tegaknya Bendera Merah Putih, mewarnai langit-langit Ibu Pertiwi, memberi simbol dan makna; kedaulatan bangsa di tangan anak bangsa itu sendiri telah kembali. Kedaulatan telah berpindah dari kolonialisme ke Indonesiaisme.
Namun, sebuah pertanyaan kita apa makna dari pernyataan Soekarno bahwa “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”. Yang sulit saat kemelut persoalan kebangsaan melanda, saat ekonomi di kuasai kaum kapitalis, persatuan yang terkoyakan, ketidakadilan, korupsi, nepotisme, kolusi, pembodohan, hingga kesenjangan sosial yang telah memperpanjang barisan kemiskinan.
Jika kita gagal melihat subtansi kemerdekaan dan cita-cita kemerdekaan masih dalam Raung “Asa” maka perayaan HUT RI hanya sebatas “Narsisme” belaka. Pengharapan kita pada pengejawantahan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga “basi” janji politi kita negasi dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Karena gagal merealisasi maksud dan tujuan kemerdekaan itu sendiri.
Mungkikah kaum narsisme paham dan menghayati setiap detak jantung kemerdekaan kita? Jika setiap perayaan hanya berkubang dalam “gincu” pencitraan narsisme, serimonial pengupacaraan, dan segala “semu-selebrasi” kemerdekaan?
TITIK TUJU ‘KEMERDEKAAN” DAN PENGHIANATANYA
“Sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala manusia, maka penjajahan di atas kemanusiaan harus dihapus, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan” (Indra)
Kemerdekaan suatu bangsa atas nama Indonesia telah diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 Wib, di Jalan Pengangsaan Timur No. 56. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ditulis oleh Ir Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik, seorang pemuda anggota Persiapan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Proklamasi dengan bunyi :
PROKLAMASI
Kami Bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoesaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoan 1945
Atas Nama Bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta
Seketika suara proklamasi kemerdekaan menjalar ke seluruh nusantara, dengan gegap gempita rakyat Indonesia menyambut dengan penuh haru dan gemberi, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia seolah dalam mimpi, perjuangan bangsa melawan penjahan terhenti. Namun kini telah 77 Tahun Kemerdekaan Indonesia persoalan dan cita-cita kemerdekaan masih mengawan di atas langit bumi pertiwi, belum terbumikan. Bahkan dalam realita kebangsaan terjadi kontras moral dengan kemerdekaan itu sendiri, persoalan kemiskinan, ketidak adilan, kesenjangan social, retaknya persatuan, Korupsi menjadi-jadi, hingga jual beli hukum terkooptasi. Benarkan segala persoalab itu menjadi hal yang menghianati cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.
Cita-cita NKRI yang tercakup dalam Pembukaan UUD 1945 yakni “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”.
Apakah cita-cita kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan telah direalisasikan dan dibumikan? Kenapa masih ada kemiskinan yang lebar? Mengapa kebodohan dan anak bangsa yang masih tidak sekolah? Kenapa keadilan masih belum mampu tercipta bahkan korupsi merajalela? Apa makna kemerdekaan setela proklamasi itu yang sesungguhnya?
Pertanyaan di atas sebuah refleksi mengevaluasi bahwa bangsa ini masih tertatih-tatih dalam mewujudkan cita-cita bangsa, bahkan terkadang bangsa ini tersungkur melawan koruptor, oligarki, dan kaum pemegang kapital. Betapa tida sumber daya alam Indonesia yang kaya berbanding terbaik dengan kondisi kemiskinan rakyat Indonesia, sebuah ironi.
Memaknai dan menginsyafi secara jujur itu mengharuskan pikiran yang tercerahkan dan hati yang terjernihkan, sehingga mampu berpikir jernih. Hal ini yang kita butuhkan saat-saat kondisi bangsa dihadapi persoalan pandemic, bahkan impac dari pandemic adanya kesulitan rakyat dalam dimensi ekonomi, aktifitas sangat terbatas. Sehingga keruntuhan berpotensi terjadi, dan bahkan inflasi bisa berimplikasi.
Merayakan harus tidak kehilangan esensi dari kemerdekan dan untuk apa kemerdekaan itu. Sehingga, semua pemangku Negara terutama; dari Jabatan Presiden, Menteri, DPR, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan Lurah. Semua “Kita” dalam bingkai keindonesiaan punya tanggungjawab sesuai fungsinya masing-masing dalam menjiwai dan bahkan mengaktualisasi cita-cita kemerdekaan Indonesia yang dimaksud.
Kemerdekaan dan Pancasila “pelaku” mafiaso dalam bahasa Indrayana adalah sebuah penghianatan yang hanya dimaniskan dalam retorika tapi dikhianati dalam perbuatan mereka. Ini prilaku yang tuna kebangsaan , hanya ingin bertenteng di atas kursi kekuasaan tapi tidak mampu membumi dalam ke-proletar-an rakyat Indonesia yang masih kesulitan kehidupannya.
Penghianatan juga dilakukan oleh anak bangsa yang rakus, menggorogoti kekayaan Indonesia tanpa melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Kemiskinan hari ini masih menganga namun masih saja kita lihat pejabat tertangkap tangan dibawa ke Komisi Pemberantahan Korupsi. Baru ini sebuah korupsi kakap, korupsi lahan sawit dengan kerugian Negara 78 T tersangka Surya Darmadi. Luar biasa “biadab”. Korupsi dan bahkan hari ini ditengah kesulitan dan penderitaan rakyat masih ada anak bangsa yang tuna kemanusiaan, tega korupsi demi memenuhi Hasrat ketidak puasannya.
HARAP!
Segala persoalan kebangsaan hari ini saat kemeriahan Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita refleksi secara kritis sebagai pembongkaran persoalan yang jujur demi membangun, mengawal, dan mendorong terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang sebenarnya. Setelah 77 tahun kemerdekaan, kita memiliki banyak persoalan bangsa, baik; dimensi social, dimensi politik, dimensi budaya, dimensi keadilan dan hukum, dimensi beragama, dan deminsi keindonesiaan itu sendiri.
Kita tidak boleh putus asa dalam memberi sumbangsih pikiran, perbuatan dan lainnya, sekalipun hanya mampu meletakkan satu batu bata bangunan masa depan Indonesia maka harus kita lakukan dengan berani. Kita tidak tahu kapan bangunan utuh dari sebuah bangsa yang dicita-citakan. Namun setidaknya kita telah berani mengkritisi kebijakan dan ketidak wajaran berlaku dilingkungan kita sendiri. Jika perlu, kritik kepala desa yang jika berapi mengkorupsi dana desa, dan memberlakukan warganya yang tidak adil.
Akhir tulisan ini, mari kita wujudkan kemerdekaan diri 100% dan melawan segala bentuk penjajahan di atas bumi Indonesia,
MERDEKA…